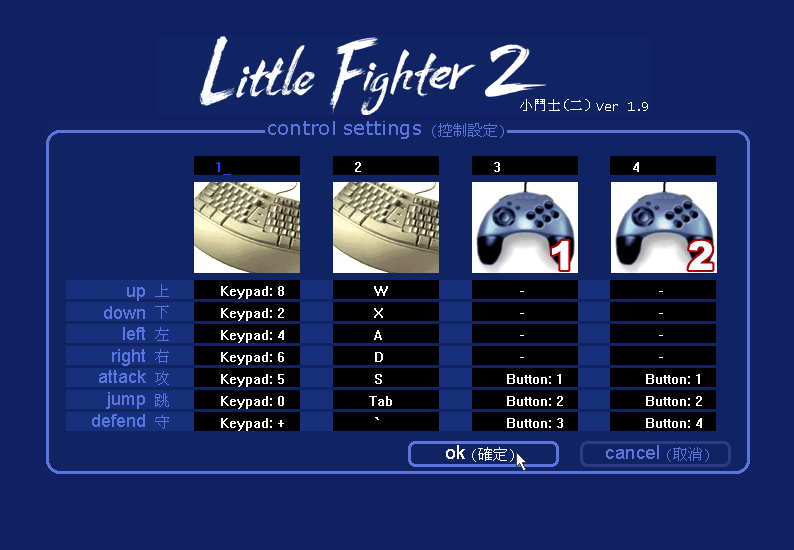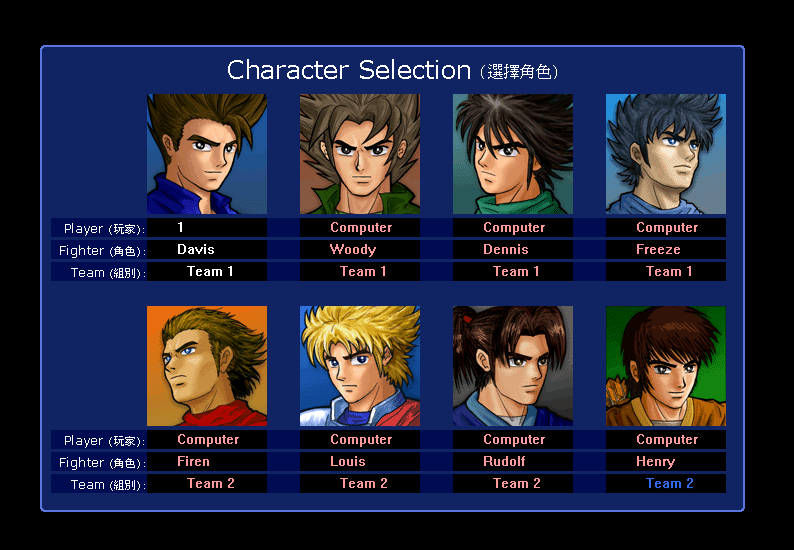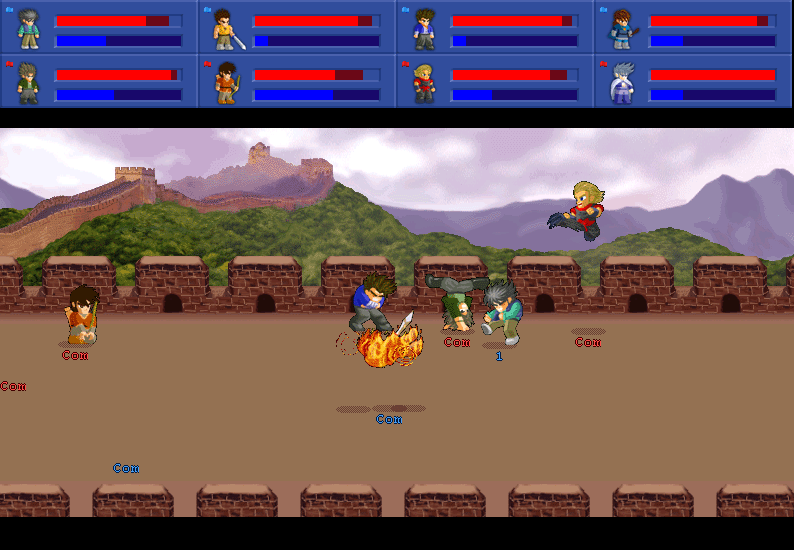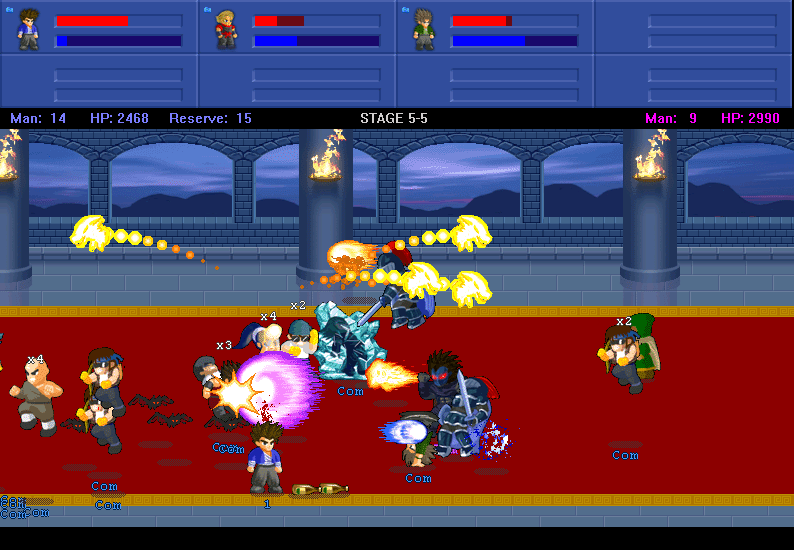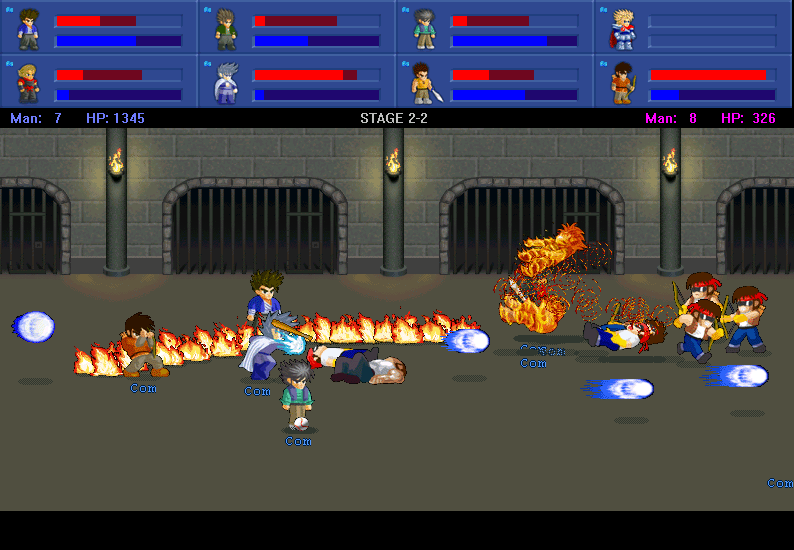BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang Masalah
pada mulanya, punjangga baru adalah nama
majalah sastra dan kebudayaan yang terbit antara tahu 1933 adanya
pelarangan oleh perintah jepang setelah tentara jepang berkuasa di
Indonesia.Adapun pengasuhnya atara lain
Sultan Takdir Alisjahbana, Armein Pane, Amir Hamzah Dan Sanusi Pane.
Jadi pujangga baru bukanlah suatu konsepsi ataupun aliran. Namun
demikian, orang-orang atau para pengarang yang asil karyanya pernah
dimuat dalam majalah itu, di nilai memiliki bobot dan cita-cita kesenian
yang baru dan mengarah ke depan.
Barang kali, hanya untuk memudahkan ingatan adanya angkatan baru
itulah maka di pakai istilah angkatan pujangga baru, yang tak lain
adalah orang-orang yang tulis-tulisanya pernah di muat di dalam masalah
tersebut. Adapun majalah itu, diterbitkan oleh pustaka rakyat, uatu
badan yang memang mempunyai perhtian terhadap masalah-masalah kesenian.
Tetapi seperti telah disinggung di atas, pada jaman pendudukan jepang
majalah pujangga baru ini dilarang pemerintah jepang dengan alasan
karena kebarat-barat.
Namun setela Indonesia merdeka, majalah ini di terbitkan lagi ( hidup 1948-1953), dengan pemimpin redaksi
Sultan Takdir Aliscahbana dan beberapa tokoh-tokoh angkatan 45 seperti
Asrul, Rivai Apin Dan S. Rukiah.
Mengingat masa hidup pujangga baru (1) itu antara tahun 1933 sampai
dengan zaman jepang, maka diperkirakan para pnyumbang karangan itu
paling tahun 1915-an dan sebelumnya.
Dengan demikian, boleh dikatakan generasi pujangga baru adalah
generasi lama. Sedangkan angkatan 45 yang kemudian menyusulnya,
merupakan angkatan baru yang jauh lebih bebas dcalam mengekspresikan
gagasan-gagasan dan kata hatinya.
I.2 Rumusan Masalah
1.2.1 bagaimana sejarah Pujangga baru?
1.2.2 Apa pengertian tentang Pujangga baru?
1.2.3 Siapa saja tokoh Pujangga Baru?
I.3 Tujuan
Tujuan yang ingin di capai dalam makalah ini di antaranya yaitu :
- Untuk mengetahui tentang sejarah dari Pujangga Baru.
- Untuk memahami tentang Pujangga Baru.
- Untuk mengetahui contoh-contoh karya Pujangga Baru.
- Untuk mengetahui tokoh-tokoh siapa saja yang termasuk angkatan Pujangga Baru.
BAB II
PEMBAHASAAN
II.1 Sejarah singkat tentang Pujangga Baru
Pada mulanya, Pujangga baru adalah nama majalah sastra dan kebudayaan
yang terbit antara tahun 1933 sampai dengan adanya pelarangan oleh
pemerintah Jepang setelah tentara Jepang berkuasa di Indonesia.
Adapun pengasuhnya antara lain Sultan Takdir Alisjahbana, Armein Pane
, Amir Hamzah dan Sanusi Pane. Jadi Pujangga Baru bukanlah suatu
konsepsi ataupun aliran. Namun demikian, orang-orang atau para pengarang
yang hasil karyanya pernah dimuat dalam majalah itu, dinilai memiliki
bobot dan cita-cita kesenian yang baru dan mengarah kedepan.
Barangkali, hanya untuk memudahkan ingatan adanya angkatan baru
itulah maka dipakai istilah Angkatan Pujangga Baru, yang tak lain adalah
orang-orang yang tulisan-tulisannya pernah dimuat didalam majalah
tersebut. Adapun majalah itu, diterbitkan oleh Pustaka Rakyat, Suatu
badan yang memang mempunyai perhatian terhadap masalah-masalah kesenian.
Tetapi seperti telah disinggung diatas, pada zaman pendudukan Jepang
majalah Pujangga Baru ini dilarang oleh pemerintah Jepang dengan alasan
karena kebarat-baratan.
Namun setelah Indonesia merdeka, majalah ini diterbitkan lagi (hidup
1948 s/d 1953), dengan pemimpin Redaksi Sutan Takdir Alisjahbana dan
beberapa tokohtokoh angkatan 45 seperti Asrul Sani, Rivai Apin dan S.
Rukiah.
Mengingat masa hidup Pujangga Baru ( I ) itu antara tahun 1933 sampai
dengan zaman Jepang , maka diperkirakan para penyumbang karangan itu
paling tidak kelahiran tahun 1915-an dan sebelumnya. Dengan demikian,
boleh dikatan generasi Pujangga Baru adalah generasi lama. Sedangkan
angkatan 45 yang kemudian menyusulnya, merupakan angkatan bar yang jauh
lebih bebas dalam mengekspresikan gagasan-gagasan dan kata hatinya.
Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang
dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa
tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa
nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah
sastra intelektual, nasionalistik dan elitis.
Pada masa itu, terbit pula majalah
Pujangga Baru yang dipimpin oleh
Sutan Takdir Alisjahbana, beserta
Amir Hamzah dan
Armijn Pane. Karya sastra di Indonesia setelah zaman Balai Pustaka (tahun 1930 – 1942), dipelopori oleh
Sutan Takdir Alisyahbana dkk. Masa ini ada dua kelompok sastrawan Pujangga baru yaitu :
- Kelompok “Seni untuk Seni” yang dimotori oleh Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah
- Kelompok “Seni untuk Pembangunan Masyarakat” yang dimotori oleh
Sutan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane dan Rustam Effendi.
Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang
dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa
tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa
nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah
sastra intelektual, nasionalistik dan elitis menjadi “bapak” sastra
modern Indonesia. Pada masa itu, terbit pula majalah “Poedjangga Baroe”
yang dipimpin oleh Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah dan Armijn
Pane. Karya sastra di Indonesia setelah zaman Balai Pustaka (tahun 1930 –
1942), dipelopori oleh Sutan Takdir Alisyahbana dkk. Masa ini ada dua
kelompok sastrawan Pujangga baru yaitu 1. Kelompok “Seni untuk Seni”
yang dimotori oleh Sanusi Pane dan Tengku Amir Hamzah dan; 2. Kelompok
“Seni untuk Pembangunan Masyarakat” yang dimotori oleh Sutan Takdir
Alisjahbana, Armijn Pane dan Rustam Effendi.
Karyasastera· Layar Terkembang oleh Sutan Takdir Alisjahbana · Tebaran
Mega · Belenggu oleh Armijn Pane · Jiwa Berjiwa · Gamelan Jiwa ·
Jinak-jinak Merpati · Kisah Antara Manusia · Nyanyian Sunyi oleh Tengku
Amir Hamzah · Buah Rindu · Pancaran Cinta oleh Sanusi Pane · Puspa Mega ·
Madah Kelana · Sandhyakala ning Majapahit · Kertajaya · Tanah Air oleh
Muhammad Yamin · Indonesia Tumpah Darahku · Ken Angrok dan Ken Dedes ·
Kalau Dewi Tara Telah Berkata · Percikan Permenungan oleh Rustam Effendi
· Bebasari · Kalau Tak Untung oleh Sariamin · Pengaruh Keadaan · Rindu
Dendam oleh J.E.Tatengkeng.
II.2 Karya- karya Pujangga Baru
Puisi Pujangga Baru: Konsep Estetik, Orientasi dan Strukturnya Oleh: Rachmat Djoko Pradopo, Prof., Dr Artikel di Jurnal Humaniora Volume XIII, No. 1/2001
Puisi Pujangga Baru adalah awal puisi Indonesia modern. Untuk
memahami puisi Indonesia modern sesudahnya dan puisi Indonesia secara
keseluruhan, penelitian puisi Pujangga Baru penting dilakukan. Hal ini
disebabkan karya sastra, termasuk puisi, tidak lahir dalam kekosongan
budaya (Teeuw, 1980:11), termasuk karya sastra. Di samping itu, karya
sastra itu merupakan
response (jawaban) terhadap karya sastra sebelumnya (Riffaterre viaTeeuw,1983:65).
Karya sastra, termasuk puisi, dicipta sastrawan. Sastrawan sebagai
anggota masyarakat tidak terlepas dari latar sosial–budaya dan
kesejarahan masyarakatnya. Begitu juga, penyair Pujangga Baru tidak
lepas dari latar sosial-budaya dan kesejarahan bangsa Indonesia. Puisi
Pujangga Baru (1920-1942) itu lahir dan berkembang pada saat bangsa
Indonesia menuntut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Oleh karena itu,
perlu diteliti wujud perjuangannya, di samping wujud latar
sosial-budayanya.
Untuk memahami puisi secara mendalam, juga puisi Pujangga Baru, perlu
diteliti secara ilmiah keseluruhan puisi itu, baik secara struktur
estetik maupun muatan yang terkandung di dalamnya. Akan tetapi, sampai
sekarang belum ada penelitian puisi Pujangga Baru yang tuntas,
sistematik, dan mendalam. Sifatnya penelitian yang sudah ada itu
impresionistik, yaitu penelaahan hanya mengenai pokok-pokoknya, tanpa
analisis yang terperinci, serta diuraikan secara ringkas.
Puisi merupakan struktur yang kompleks. Oleh karena itu, dalam
penelitian puisi Pujangga Baru digunakan teori dan metode struktural
semiotik. Kesusastraan merupakan struktur ketandaan yang bermakna dan
kompleks, antarunsurnya terjadi hubungan yang erat (koheren). Tiap unsur
karya sastra mempunyai makna dalam hubungannya dengan unsur lain dalam
struktur itu dan keseluruhannya (Hawkes, 1978: 17—18). Akan tetapi,
strukturalisme murni yang hanya terbatas pada struktur dalam (inner
structure) karya sastra itu mengasingkan relevansi kesejarahannya dan
sosial budayanya (Teeuw, 1983: 61). Oleh karena itu, untuk dapat
memahami puisi dengan baik serta untuk mendapatkan makna yang lebih
penuh, dalam menganalisis sajak dipergunakan strukturalisme dinamik
(Teeuw, 1983: 62), yaitu analisis struktural dalam kerangka semiotik.
Karya sastra sebagai tanda terikat kepada konvensi masyarakatnya. Oleh
karena itu, karya sastra tidak terlepas dari jalinan sejarah dan latar
sosial budaya masyarakat yang menghasilkannya, seperti telah terurai di
atas.
Di samping itu, untuk memahami struktur puisi Pujangga Baru, perlu
juga diketahui struktur puisi sebelumnya, yaitu puisi Melayu lama yang
direspons oleh puisi Pujangga Baru.
Buku Sejarah Sastra Indonesia Modern Jilid 1 karya Bakri Siregar
(1964) memperlihatkan bahwa subjektivitas penulis sejarah—termasuk
sejarah sastra Indonesia—senantiasa tampak dalam buku yang
dihasilkannya.
Bakri Siregar merupakan pimpinan pusat Lembaga Kebudayaan Rakyat
(Lekra) yang juga menjabat sebagai Ketua Akademi Sastra dan Bahasa
“Multatuli” Jakarta dan Guru Besar Sastra Indonesia Modern di
Universitas Peking. Pascaperistiwa G30S 1965, Bakri Siregar termasuk
sastrawan Lekra yang ditahan tanpa diadili dan baru dibebaskan pada
1977.
Menyusul penahanannya adalah dilarangnya buku sejarah yang ditulisnya
itu. Hingga kini, tidak akan ada buku Sejarah Sastra Indonesia Modern
Jilid 2 dari sang penulis, karena Bakri Siregar telah meninggal pada 19
Juni 1994. Buku Sejarah Sastra Indonesia Modern Jilid 1 ini berisi masa
awal sastra Indonesia, masa Balai Pustaka, hingga masa Pujangga Baru
(1930-an).
Sebenarnya topik pembicaraan belum masuk periode 1960-an, namun dalam
pengantarnya Bakri Siregar telah menyinggung konsep kesenian Lekra dan
sastrawan Manifes Kebudayaan (Manikebu). Mengenai cakupan khazanah
sastra Indonesia, saya sangat sependapat dengan Bakri Siregar. Bahwa
pengertian sastra Indonesia itu mencakup naskah-naskah Melayu di
Indonesia hingga akhir abad ke-19.
Dalam bahasa A Teeuw, karya sastra semacam ini dinamakan “sastra di
Indonesia”. Bakri Siregar juga memasukkan karya sastra yang berbahasa
Melayu Tionghoa ke dalam khazanah sastra Indonesia. Hanya saja, saat ia
menulis buku Sejarah Sastra Indonesia Modern Jilid 1, ia merasa
kesulitan mendapatkan bahan-bahan itu.
Zuber Usman (dalam Siregar, 1964), mengatakan bahwa Abdullah bin
Abdulkadir Munsji yang hidup di abad ke-19 merupakan penutup zaman lama
dan Abdullah dapat diumpamakan sebagai cahaya fajar zaman baru yang
mulai menyingsingkan sinarnya di ufuk zaman itu.
Tampaknya Bakri Siregar enggan memasukkan Abdullah sebagai tokoh awal
sastra Indonesia modern karena setelah membaca memoarnya, Hikayat
Abdullah, Bakri Siregar menilai sikap Abdullah yang dalam batas tertentu
mempunyai segi positif dalam mengkritik kaum bangsawan Melayu dan
praktik onar para raja, tapi di sisi lain Abdullah terlalu memuji dan
kagum pada penjajah Inggris dengan menamakan mereka tokoh-tokoh
kemanusiaan yang ikhlas dan bijaksana.
Sikap seperti itu, menurut Bakri Siregar, sebagai kompleks rasa
rendah diri yang terlalu besar pada diri Abdullah dalam menghadapi orang
kulit putih, hingga praktis merendahkan bangsanya dan bangsa-bangsa
lain di Asia.
Menurut Bakri Siregar ada tiga sastrawan yang menjadi tokoh awal
sastra Indonesia modern. Mereka adalah Mas Marco Kartodikromo, Semaun,
dan Rustam Effendi. Karya-karya Mas Marco Kartodikromo, baik dalam
bahasa Jawa maupun dalam bahasa Indonesia secara tegas pertama kali
melemparkan kritik terhadap pemerintah jajahan serta kalangan feodal.
Dua karya Mas Marco yang menonjol adalah Student Hidjo (1919) dan
Rasa Merdeka (1924). Karena isinya berupa kritik terhadap imperialisme
Belanda dan antifeodalisme, karya-karya Mas Marco dilarang pemerintah
kolonial Belanda. Sebagai sastrawan dan juga wartawan yang revolusioner,
Mas Marco sering keluar masuk penjara, dan meninggal di tanah
pembuangan Digul.
Semaun menghasilkan novel Hikayat Kadirun pada 1924. Dalam novel
tersebut, Semaun membayangkan kehidupan dalam masyarakat masa depan yang
lebih baik dari keadaannya saat itu. Masyarakat masa itu yang
digambarkan adalah masyarakat yang berada dalam belenggu penjajahan.
Dengan demikian, apa yang dianggap baik di hari depan oleh penulis,
dianggap musuh oleh penjajah. Pada 1932, Semaun menyumbangkan artikel
dalam Ensiklopedi Kesusastraan yang terbit di Moskow.
Semaun antara lain menulis, “Hikayat Kadirun didasarkan untuk melawan
rezim penjajah Belanda. Roman ini disita dan setelah pemberontakan
tahun 1926/1927 dipandang sebagai buah ciptaan kesusastraan di bawah
tanah. Oplah sastra revolusioner sangat terbatas, tidak lebih dari
1.500-2.000 buah. Buku-buku itu dicetak di percetakan Partai Komunis dan
serikat buruh.” (Siregar, 1964).
Rustam Effendi menulis lakon Bebasari pada 1926. Lakon ini berisi
sindiran terhadap penjajah dan menggelorakan semangat pemuda dan rakyat.
Simbol-simbol wayang digunakan Rustam Effendi untuk mengkritik
penguasa. Rahwana, misalnya, melambangkan sifat bengis kaum penjajah.
Sementara Bebasari melambangkan cita-cita kemerdekaan. Bebasari
mengatakan di akhir lakon, “Asmara sayap usaha yang tinggi/ Asmara
kepada bangsa sendiri.”
Ketiga tokoh awal mula sastra Indonesia versi Bakri Siregar itu
mendapat kendala di zaman Belanda. Karya-karya ketiga sastrawan
revolusioner itu dilarang oleh Belanda. Bahkan Kepala Balai Pustaka A
Rinkes menyebut karya mereka sebagai bacaan liar.
Dalam buku Sejarah Sastra Indonesia Modern Jilid 1 itu, Bakri Siregar
juga menjelaskan adanya beberapa pengaruh dari luar terhadap
perkembangan sastra Indonesia modern. Pertama, pengaruh Hindu dan Islam,
yang mempengaruhi awal-awal perkembangan sastra Indonesia. Dalam
artikel “Dua Kiblat dalam Sastra Indonesia” (Sambodja, 2005).
Hal ini terlihat dari naskah-naskah berbahasa Melayu dan
naskah-naskah berbahasa Jawa Kuno. Kedua, sikap revolusioner yang muncul
dalam karya-karya sastra Indonesia awal itu merupakan pengaruh dari Uni
Soviet dan Tiongkok; antara lain melalui karya Maxim Gorki, tokoh
realisme sosialis, dan Lu Hsun, pelopor sastra Tiongkok modern.
Ketiga, pengaruh dari Barat, terutama Belanda, yakni komunitas De
Tachtigers yang menginspirasi sastrawan-sastrawan Pujangga Baru.
Sastrawan Eduard du Perron dan Hendrik Marsman sangat mempengaruhi
perkembangan kepenyairan Chairil Anwar. Multatuli alias Eduard Douwes
Dekker (1860) yang menulis buku Max Havelaar juga mempengaruhi sastrawan
revolusioner Indonesia. “Kalau bukuku diperhatikan dengan baik, dan
disambut dengan baik, maka tiap sambutan baik akan menjadi kawanku
menentang pemerintah,” tulis Multatuli.
Bagaimana dengan Manikebu? Bakri Siregar mengatakan, “Dalam
meniadakan dan membendung semangat revolusi, mereka mengemukakan
konsepsi humanisme universal, sejalan dengan usaha neokolonialisme dalam
mempertahankan kepentingan di Indonesia, menganjurkan eksistensialisme
(‘filsafat iseng’ dan ‘filsafat takut’), serta memupuk individualisme
dan pesimisme, menjadikan sastrawan dan seniman kosmopolit dan
antipatriotik, tanpa menyatukan diri dengan perjuangan bangsanya.”
(Siregar, 1964: 13-14).
II.3 Angkatan Pujangga Baru
- Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya
sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis
sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang
menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan.
- Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia.
- Angkatan Pujangga Baru (1930-1942) dilatarbelakangi oleh kejadian bersejarah “Sumpah Pemuda” pada 28 Oktober 1928.
- Ikrar Sumpah Pemuda 1928:
-
- Pertama Kami poetera dan poeteri indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe, tanah Indonesia.
-
- Kedoea Kami poetera dan poeteri indonesia, mengakoe berbangsa jang satoe, bangsa Indonesia.
-
- Ketiga Kami poetera dan poeteri indonesia, mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Indonesia.
- Melihat latar belakang sejarah pada masa Angkatan Pujangga
Baru, tampak Angkatan Pujangga Baru ingin menyampaikan semangat
persatuan dan kesatuan Indonesia, dalam satu bahasa yaitu bahasa
Indonesia.
- Pada masa ini, terbit pula majalah Poedjangga Baroe yang
dipimpin oleh Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah dan Armijn
Pane.
- Pada masa Angkatan Pujangga Baru, ada dua kelompok sastrawan Pujangga baru yaitu:
-
- Kelompok “Seni untuk Seni”
-
- Kelompok “Seni untuk Pembangunan Masyarakat”
- Ciri-ciri sastra pada masa Angkatan Pujangga Baru antara lain sbb:
-
- Sudah menggunakan bahasa Indonesia
-
- Menceritakan kehidupan masyarakat kota, persoalan intelektual, emansipasi (struktur cerita/konflik sudah berkembang)
-
- Pengaruh barat mulai masuk dan berupaya melahirkan budaya nasional
-
- Menonjolkan nasionalisme, romantisme, individualisme, intelektualisme, dan materialisme.
- Salah satu karya sastra terkenal dari Angkatan Pujangga Baru adalah Layar Terkembang karangan Sutan Takdir Alisjahbana.
- Layar Terkembang merupakan kisah roman antara 3 muda-mudi; Yusuf, Maria, dan Tuti.
-
- Yusuf adalah seseorang mahasiswa kedokteran tingkat akhir yang menghargai wanita.
-
- Maria adalah seorang mahasiswi periang, senang akan pakaian bagus, dan memandang kehidupan dengan penuh kebahagian.
-
- Tuti adalah guru dan juga seorang gadis pemikir yang berbicara
seperlunya saja, aktif dalam perkumpulan dan memperjuangkan
kemajuan wanita.
- Dalam kisah Layar Terkembang, Sutan Takdir Alisjahbana ingin menyampaikan beberapa hal yaitu:
-
- Perempuan harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat
memberikan pengaruh yang sangat besar didalam kehidupan berbangsa
dan bernegara dengan demikian perempuan dapat lebih dihargai
kedudukannya di masyarakat.
-
- Masalah yang datang harus dihadapi bukan dihindarkan dengan
mencari pelarian. Seperti perkawinan yang digunakan untuk pelarian
mencari perlindungan, belas kasihan dan pelarian dari rasa
kesepian atau demi status budaya sosial.
- Selain Layar Terkembang, Sutan Takdir Alisjahbana juga membuat sebuah puisi yang berjudul “Menuju ke Laut”.
- Puisi “Menuju ke Laut” karya Sutan Takdir Alisjahbana ini
menggunakan laut untuk mengungkapkan h ubungan antara manusia,
alam, dan Tuhan.
- Ada pula seorang sastrawan Pujangga Baru lainnya, Sanusi Pane
yang menggunakan laut sebagai sarana untuk mengungkapkan hubungan
antara manusia, alam, dan Tuhan.
- Karya Sanusi Pane ini tertuang dalam bentuk puisi yang berjudul “ Dalam Gelombang”.
- Ditinjau dari segi struktural, ada persamaan struktur antara
puisi Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi Pane yaitu pengulangan
bait pertama pada bait terakhir.
- Sementara itu, ditinjau dari segi isi, tampak ada perbedaan
penggambaran laut dalam puisi Sutan Takdir Alisjahbana dan Sanusi
Pane.
- Jika Sutan Takdir Alisjahbana menggambarkan laut sebagai sebuah
medan perjuangan, Sanusi Pane menggambarkan laut sebagai suatu
tempat yang penuh ketenangan.
· Contoh Puisi Angkatan Pujangga Baru
- Kami telah meninggalkan engkau,
- Tasik yang tenang tiada beriak,
- diteduhi gunung yang rimbun,
- Sebab sekali kami terbangun,
- Ombak riak berkejar-kejaran
- di gelanggang biru di tepi langit.
- Pasir rata berulang di kecup,
- tebing curam ditentang diserang,
- dalam bergurau bersama angin,
- dalam berlomba bersama mega.
… Aku bernyanyi dengan suara Seperti bisikan angin di daun Suaraku
hilang dalam udara Dalam laut yang beralun-alun Alun membawa bidukku
perlahan Dalam kesunyian malam waktu Tidak berpawang tidak berkawan
Entah kemana aku tak tahu Menuju ke Laut Oleh Sutan Takdir Alisjahbana
Dibawa Gelombang .
Oleh Sanusi Pane
- Amir Hamzah diberi gelar sebagai “Raja Penyair” karena mampu
menjembatani tradisi puisi Melayu yang ketat dengan bahasa
Indonesia yang sedang berkembang. Dengan susah payah dan tak selalu
berhasil, dia cukup berhasil menarik keluar puisi Melayu dari puri-puri
Istana Melayu menuju ruang baru yang lebih terbuka yaitu bahasa
Indonesia, yang menjadi alasdasar dari Indonesia yang sedang
dibayangkan bersama.
Selain Sutan Takdir Alisjahbana, ada pula tokoh lain yang terkenal
dari Angkatan Pujangga Baru sebagai “Raja Penyair” yaitu Tengku Amir
Hamzah .
· Sastrawan dan Hasil Karya
- Sastrawan pada Angkatan Pujangga Baru beserta hasil karyanya antara lain sbb:
-
- Sultan Takdir Alisjahbana
-
-
- Contoh: Di Kakimu, Bertemu
-
-
- Contoh: Andang Teruna (fragmen)
-
-
- Contoh: Bunda dan Anak, Lagu Waktu Kecil
-
-
- Contoh: Rindu, Hidup Baru
-
-
- Contoh: Berpisah, Kehilangan Mestika (fragmen)
· Sastrawan dan Hasil Karya
-
-
- Contoh: Sunyi, Dalam Matamu
-
-
- Contoh: Ladang Petani, Sawah
-
-
- Contoh: Bagaimana Sebab Aku Terdiam
-
-
- Contoh: Amanat, Kupu-kupu
BAB III
PENUTUP
III.1 Kesimpulan
Punjangga Baru merupakan nama majalah sastra dan
kebudayaan yang terbit antara tahu 1933 adanya pelarangan oleh perintah
jepang setelah tentara jepang berkuasa di Indonesia.Adapun pengasuhnya
atara lain
Sultan Takdir Alisjahbana, Armein Pane, Amir Hamzah Dan Sanusi Pane.
Jadi pujangga baru bukanlah suatu konsepsi ataupun aliran. Namun
demikian, orang-orang atau para pengarang yang asil karyanya pernah
dimuat dalam majalah itu, di nilai memiliki bobot dan cita-cita kesenian
yang baru dan mengarah ke depan. Angkatan Pujangga Baru muncul sebagai
reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap
karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra
yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan.
III.2 Saran
Diharapkan paper ini dapat bermanfaat bagi kita
semua khususnya para calon guru atau calon pendidik agar menjadi
pendidik yang professional. Dan sebagai Mahasiswa jurusan bahasa
indonsia, kita juga perlu memahami tengtan puisi, yaitu Pujangga Baru
maupun tentang angkatan sastra yang lainya. Karena kita sebagai calon
guru bahasa Indonsia akan mengajarkan anak didik tentang sastra dan
pelajaran Bahasa Indonesia yang lainya.
DAFTAR PUSTAKA
- Internet,
www. Google. Com.
Pujangga Baru Sastra
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………………… i
Daftar Isi ………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang…………………………………………… 1
1.2 Rumusan Masalah………………………………………… 1
1.3 Tujuan……………………………………………………. 2
BAB II PEMBAHASAN
2.1 Sejarah singkat tentang Pujangga Baru…………………… 3
2.2 Karya-karya Pujangga Baru………………………………. 5
2.3 Angkatan Pujangga baru……………………………..…… 9
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan………………………………………………. 15
3.2 Saran…………………………………………………….. 15